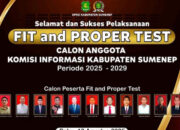Oleh : Arafah Pramasto*

Istilah Local Genius atau yang lebih dikenal sebagai kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Ahmad Muhli Junaidi (2017) menambahkan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat. Nazarudin Zainun (2015) melengkapi dengan mengutip dari pendapat Haryati Soebadio menyatakan bahwa kearifan lokal adalah indentitas atau kepribadian budaya bangsa (cultural identity) yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal sendiri umumnya tidak berwujud kebendaan, namun lebih kepada berbagai nilai yang ditinggikan dalam sebuah masyarakat.
Bagaimana bisa menjadikan sosok Rato Ronggosukowati sebagai kearifan lokal? Jawabannya karena Rato Ronggosukowati sebagai figur sejarah salah satu kerajaan yang pernah ada di Madura telah mewariskan pengetahuan yang luhur dalam aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Pamekasan-Madura di masa modern ini. Cara yang dapat diambil untuk menjadikan sosok Ronggosukowati sebagai Local Genius atau kearifan lokal Madura adalah dengan mendedah kisah kepemimpinan beliau yang terekam dalam sejarah, sehingga didapat beberapa poin penting untuk kemudian dimaknai agar diperoleh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kearifan lokal yang akan diperoleh dari kisahnya sarat akan teladan yang baik bagi para pemimpin, politisi, maupun rakyat Madura secara umum. Untuk itu, sebelumnya kita perlu mengetahui siapakah sosok Ronggosukowati sebenarnya.
1. Siapakah Rato Ronggosukowati?
Pangeran Sukowati adalah putra dari seorang penguasa Keraton Pamellingan bernama Raden Nugroho yang bergelar Rato Bonorogo. Kakak Pangeran Sukowati menggantikan posisi kakeknya yang bernama Arya Pramono untuk berkuasa di Keraton Madegan (Sampang). Nenek Pangeran Sukowati adalah Ratu Nyi Banu istri Arya Pramono sebagai penguasa Pamellingan sebelum digantikan oleh Rato Bonorogo. Pangeran Sukowati juga dikenal dengan nama Pangeran Arya Seno, ia kemudian memperoleh gelar Ronggo (jabatan stingkat di bawah adipati) setelah kakakya berkuasa di Madegan. Pangeran Ronggosukowati sempat tinggal di Madegghan, masuk dan belajar Islam dari Pandhita Mpu Bagenno. Bila dirunut terus ke atas, Ronggosukowati adalah keturunan penguasa Majapahit yakni Bhre Kertabhumi (Brawijaya V) melalui dua jalur Pangeran Lembu Petteng dan Arya Damar.
Ayah Ronggosukowati, Rato Bonorogo semasa hidupnya masih belum berkenan memeluk Islam. Suatu ketika Ronggosukowati mendapatkan sebuah ucapan yang bisa dikatakan cukup mengagetkan dari sang ayah, â€Sebenarnya aku sudah memeluk Islam, itu dapat dibuktikan (kebenarannya) nanti saat aku menemui ajal, maka akan terjadi gempa yang cukup besar…†Benar apa yang dikatakan Rato Bonorogo, saat ia wafat terjadilah gempa yang cukup besar; ini diyakini sebagai tanda keislamannya. Pangeran Sukowati naik tahta di Keraton Pamellingan meggantikan ayahnya pada 1530. Ronggosukowati yang akhirnya bergelar Rato itu, memindahkan Keraton Pamellingan ke sebuah tempat baru yang bernama Keraton Mandhilaras dan ini menandai pendirian kota Pamekasan. Semenjak itu, kerajaan yang dipimpin oleh Rato Ronggosukowati lebih dikenal dengan nama Kerajaan Pamekasan bukan Pamellingan. Kepemimpinan Ronggosukowati di Pamekasan mempunyai beberapa dimensi yang penting untuk diingat yakni dalam masalah pembangunan fisik, penghargaan pada ulama, dan pertahanan wilayah.
2. Pembangunan Fisik
Kecintaan Rato Ronggosukowati kepada Islam ditunjukkan dengan pendirian sebuah Maseghit (Masjid) yang tidak jauh dari Keraton Mandhilaras. Masjid yang ia buat sengaja ditempatkan di pinggir sungai guna memudahkan orang mengambil air wudhu’. Awalnya beberapa orang dipilih untuk menjaga dan merawat masjid itu. Beberapa di antaranya memilih bertempat tinggal di dekat masjid. Selanjutnya bertambah banyaklah orang-orang yang bertempat tinggal di kawasan tersebut sehingga berkembang menjadi Kampong Maseghit (Kampung Masjid). Kemudian, Rato Ronggosukowati memutuskan perawatan masjid dikelola oleh seorang pejabat yang berpangkat “Tumenggungâ€. Karena telah terjadi perubahan kepengurusan yang ditangani oleh pejabat kerajaan, banyak yang menyebut masjid tersebut sebagai Maseghidda Rato (Masjid Raja) dan berubah penyebutannya lagi menjadi Maseghit Jami’ (Masjid Jama’ah) ketika bangunan itu diperbesar.
Dahulu di depan masjid itu dibangun sebuah taman yang memiliki lorong-lorong menyerupai lafadz Allah, tujuannya agar masyarakat kerajaan ini selalu berada di jalan Allah. Selain pendirian masjid untuk pusat pemerintahan yang baru, Ronggosukowati juga terkenal akan proyek pembangunan yang massif. Ia mendirikan pemukiman di kota Pamekasan untuk para Panyongkol Pajunga Rato (Pembawa Payung Raja) dan kini dikenal sebagai Kampong Kolpajung, dan pemukiman untuk para Kabula/Kawula yang disebut Kampong Kowel. Dengan adanya pemukiman-pemukiman berdasarkan profesi tertentu tadi, Ronggosukowati telah membuktikan bahwa para pekerja/pegawainya itu menandai penghargaan kepada mereka yang telah bekerja untuk urusan istana. Selain itu, dengan adanya perkampungan tersebut segala urusan pemerintahan yang berpusat di keraton dapat dijalankan dengan baik karena mudahnya koordinasi dari pihak keraton.
3. Penghormatan pada Ulama
Suatu ketika di masa pemerintahan Rato Ronggosukowati terjadi kemarau yang berkepanjangan selama beberapa tahun. Maka Rato memutuskan untuk melakukan semedi. Di dalam semedinya itu ia bertemu dengan seorang tua renta yang menjelaskan bahwa penyebab kemarau di kerajaannya adalah dua orang yang bertapa di bawah pepohonan, di sebuah hutan yang terdapat rawa-rawa. Keesokan harinya diutus seorang patih untuk mencari dua orang itu ke arah timur keraton. Patih itu berhasil menemukan dua orang yang dicari di sebuah tempat sesuai dengan arahan Rato Ronggosukowati. Sang patih kemudian bertanya kepada kedua orang itu,
â€Siapa kisanak berdua ini? Apa tujuan kalian bertapa?â€
Salah seorang di antaranya menjawab,
â€Saya Abdurrahman, murid dari Kiai Ajhi Ghunong di Sampang, saya di sini bukan untuk bertapa, tetapi oleh Kiai, saya disuruh bertempat tinggal di sini. Selama saya belum memiliki tempat berteduh (yang mapan), saya berdoa kepada Allah agar tidak turun hujan. Di tempat ini saya ditemani kemenakan saya yang bernama Bindhara Bhungso…â€
Sang patih segera kembali ke keraton dan menyampaikan temuannya. Rato segera menugaskan beberapa orang untuk membangun sebuah padepokan guna ditinggali oleh dua orang itu. Setelah padepokan itu dibuat, hujan lebat segera mengguyur Pamekasan. Orang-orang pun mulai banyak berdatangan ke tempat Abdurrahman untuk belajar mengaji, ia juga kemudian bergelar K(ya)e’ Aghung Rabeh (Kiai Agung (yang tinggal di) Rawa-Rawa). Makamnya juga masih sering dikunjungi hingga kini yang terletak di Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu.
Ceritera tentang Kyae Aghung Rabeh ini menggambarkan sebentuk kedermawanan raja kepada kaum agamawan. Selain masalah kedermawanan, sesungguhnya perhatian penguasa kepada kaum agamawan adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dilalaikan mengingat bahwa spiritualitas rakyat yang baik ialah karena bimbingan para ulama. Pemimpin tidak boleh hanya sekadar melakukan pembangunan fisik yang sifatnya monumental namun malah melupakan pembangunan karakter manusia/rakyatnya agar mencapai ketinggian moral.
4. Pertahanan
Sebagai seorang Muslim, Rato Ronggosukwati menyadari pentingnya melindungi rakyatnya sebagaimana dalam QS.Al-Hajj, 22:39 disebutkan mengenai kewajiban mempertahankan diri apabila diperangi, secara usul fiqh hal ini terkait dengan pemeliharaan jiwa dan harta. Sang Rato turut membangun markas prajurit Pamekasan yang berdekatan dengan Keraton Mandhilaras untuk menjaga tempat tinggal keluarga kerajaan dan terkadang digunakan sebagai bui/penjara. Markas prajurit yang terletak di sebelah timur Keraton juga berfungsi sebagai asrama dan tempat pendidikan para pemuda dan calon prajurit yang tangguh. Pembangunan-pembangunan yang diusahakan oleh Ronggosukowati dalam bidang pertahanan nampaknya adalah hal yang biasa dalam masalah pemerintahan.
Dalam sejarah Pamekasan pernah terjadi sebuah ancaman yang akan mengganggu keamanan rakyat dan lebih jauh lagi ialah bagi kedaulatan Pamekasan sebagai kerajaan yang merdeka. Ancaman yang dimaksudkan adalah invasi dari kerajaan Bali terhadap Pamekasan pada tahun ke-30 masa pemerintahan Ronggosukowati. Penyerangan pihak Bali yang dicatatkan secara singkat dalam kesejarahan Madura itu dimulai saat terjadi pendaratan di beberapa tempat di Madura yang tersebar dari Bangkalan hingga Sumenep. Mereka memakai perahu yang menyerupai kapal Tiongkok yaitu jenis Jung (Madura : Jhung) melalui aliran sungai dari pinggir pantai dan ditambatkan sebelum mendarat di pinggir sungai dekat pusat kota. Pasukan Pamekasan yang telah menanti langsung menyongsong mereka, sehingga dengan cepat pasukan Bali dikalahkan. Di antara pasukan Bali ada yang kembali ke kapal-kapalnya, ada juga yang melarikan diri ke hutan selatan kota Pamekasan, dan di antaranya ada yang meminta penghidupan kepada rakyat Pamekasan di dekat tempat mereka mendarat. Tempat di mana pasukan Bali menambatkan (Madura: acangcang) Jung-jung-nya, kini disebut Desa Jhungcangcang. Hingga sekarang masih ditemukan keturunan pasukan Bali di desa tersebut.
5. Kesimpulan
Ronggosukowati adalah sosok pemimpin paripurna yang dapat dicontoh sebagai teladan yang baik pada bidang pemerintahan. Pembangunan fisik yang beliau usahakan lebih diarahkan kepada tujuan kemasyarakatan dan keagamaan. Meskipun seperti lumrahnya para penguasa-penguasa negara monarki yang dilayani oleh banyak pembantu, Rato Ronggosukowati tidak melupakan kewajibannya untuk menyediakan pemukiman bagi para kawula istana. Selaku raja yang beragama Islam, Ronggosukowati ikut membangun sebuah masjid besar untuk kebutuhan ibadah serta penanggung jawab dari rumah ibadah itu ialah pejabat kerajaan setingkat Tumenggung. Kepada kaum ulama, raja Pamekasan ini tidak mengabaikan kebutuhan mereka dan bahkan dengan inisiatifnya sendiri Kyae Aghung Rabeh diberi bantuan pendirian padepokan agar dapat mengajarkan agama.
Masalah pertahanan negara ia perhatikan dengan baik melalui pembangunan markas militer yang juga bisa dipakai sebagai penjara untuk orang-orang yang melanggar hukum. Dari kejadian invasi/penyerangan Bali terhadap Pamekasan kita memperoleh sedikit gambaran bahwa bidang transportasi sungai ikut diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu saat Bali melakukan penyerbuan, nampaknya jajaring informasi kemiliteran (telik sandi) juga berfungsi dengan baik karena pasukan Pamekasan telah bersiap untuk menghadapi musuh dan akhirnya dapat mengalahkan mereka. Sisa pasukan Bali yang tidak sempat melarikan diri juga dijaga keselamatannya meskipun secara kultur maupun agama berbeda dengan Kerajaan Pamekasan, tidak ada pasukan Bali yang menyerah dibunuh hanya karena mereka tidak beragama Islam; sisa pasukan Bali dengan keinginannya sendiri kemudian memeluk Islam serta menjadi bagian dari rakyat Pamekasan. Teladan Rato Ronggosukowati adalah kearifan lokal Madura yang mengajarkan pentingnya totalitas dalam bekerja tanpa melalaikan kepedulian sesama, keberanian untuk menjadi pemenang tanpa merendahkan yang kalah, serta keteguhan pada prinsip tanpa mengabaikan toleransi pada beragam identitas.
Referensi :
Fauzi, Jakfar Shodiq, Kemilau Bukit Batu Ampar: Sebuah Manaqib Buyut Batu Ampar, Surabaya: Penerbit Sinar Terang, 2013.
Junaidi, Ahmad Muhli, Guru Menulis, Jakarta: CV Pustaka Tunggal, 2017.
Ma’arif, Syamsul, The History of Madura, Yogyakarta: Araska, 2015.
Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan: Dinas P & K, 2006.
Zainun, Nazarudin (Ed.), Antropologi dan Sejarah dalam Kearifan Tempatan, Pulau Pinang: Universiti Malaysia Press, 2015.
* Freelance Writer dan History Blogger asal Madura yang berdomisili di Sumatera.