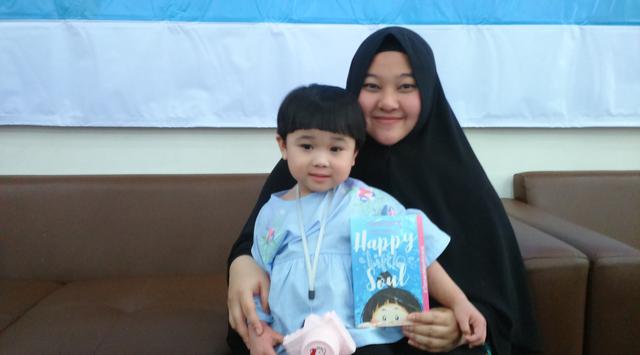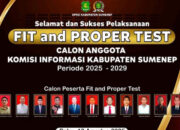Judul Buku  : Beralamat di Indonesia
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penulis          : Priyadi
Penerbit        : Bilik Literasi
Cetakan        : 2017
Tebal             : 60 hlm
ISBNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : –
Peresensi   : Ainyyaturrahmah*     Â
Sajian gagasan bertema keindonesiaan kian santer belakangan ini. Gagasan ini mengacu pada kondisi gejolak sosial politik di Indonesia. Berdalih demi rawatan nasionalisme pemerintah pun jadi bagian penting sebagai penebar gaasan itu melalui beberapa kebijakan seperti slogan, iklan, seminar, serta jargon-jargon beraroma politik.
Gagasan keindonesiaan dibangun meski berjarak dengan pembacaan sosial budaya dan sejarah. Ancaman radikalisasi agama misalnya, dan kepentingan ambisi hidup maju memicu gerakan politik, ekonomi, dan pendidikan lebih agresif dan impresif. Indonesia semakin gaduh oleh aneka ragam kebijakan, korupsi, wisata, dan tentu saja politik.
Kita yang suntuk membaca kegaduhan Indonesia, bisa mendapat secuil pencerahan dari buku Beramalat di Indonesia buah tangan Priyadi. Buku ini mendefinisakan Indonesia melalui acuan ke masa lalu dan kaitannya dengan persoalan yang lebih subtansial dan mendasar dari berkehidupan bernegara. Misalnya tentang sawah dan musik dangdut.
Satu esai berjudul Menjadi Indonesia atau Modern? mengajukan persoalan identitas hidup bernegara. Esai ini sekaligus mengingatkan kita tentang kesadaran hidup beserta kecenderungan pragmatis yang justru kerap kali melibas tata nilai lokal berpamrih materi dan kemauan hidup maju selaras dengan perkembangan teknologi informasi.
Priyadi mendeskripsikan keindonesiaan dan kemodernan itu dalam bingkai sejarah di masa yang jauh sebelum kemerdekaan. Masa ketika identitas menjadi pertaruhan hidup atau mati, penjara, dan pembuangan. Bahkan identitas menjadi satu perlawanan terhadap kolonialisme. Orang-orang Pribumi yang belajar ke Belanda mengalami pilihan cara hidup antara modern sebagai mana yang ditemukan di Belanda atau tetap mempertahankan identitas keindonesiaannya.
Pola hidup di zaman kolonial yang dilakukan oleh student-student Indonesia di Belanda terbiaskan melalui cara berpakaian, makanan, minuman dan buku-buku bacaan: ambisi merdeka dan menjadi Indonesia adalah keinginan untuk setara dengan bangsa Eropa. Kaum Bumiputera berhasrat untuk modern dan egaliter, baik itu dalam gaya busana, transportasi, bhasa, makanan, juga buku bacaan (hal. 23).
Tema keindonesiaan terus bergulir meski buku ini tentu jauh dari cap buku bacaan penting menyangkut persoalan Indonesia belakangan ini. Namun, kejelian Priyadi menangkap tema-tema keindonesiaan kentara pada gagasan esai dengan perspektif budaya disertai dengan limpahan referensi yang memikat dan informatif. Indonesia sengaja disuguhkan kepada pembaca melalui jalan perenungan sejarah agar angan tentang Indonesia tidak melulu tentang kemajuan tanpa memparsialkan hakikat hidup bernegara dalam bingkai nasionalisme.
Kita dapat membaca bagaimana Priyadi mengkritisi budaya joget di tengah-tengah kita, utamanya yang sering kita lihat di televisi setiap saat. Esai berjudul Bung Karno, Joget, dan Indonesia dengan inpresif menerangkan lakon joget dan dampaknya dalam kehidupan kita. Joget bukan semata lenggokan tubuh beriring debuman musik.
Dalam pandangam Priyadi, kita sering alpa memaknai joget. Apalagi tahun-tahun belakangan ini joget menjadi tren ketika ditiru oleh semua orang. Sebut saja misalnya goyang dumang, goyang itik, goyang pinguin, dan lain-lain. Joget jadi bahan komuditas. Indonesia pun jadi negeri para penjoget.
Kita justru lupa atau malah tidak tahu jika joget ternyata tentang nasionalisme. Dalam catatan Priyadi, Bung Karno adalah seorang penjoget bahkan betah berjoget selama 3 jam tanpa henti. Kegandrungan Bung Karno berjoget membuat ajudan pribadinya juga memiliki tugas bermain musik mengiringi Bung Karno berjoget, sehingga kemudian terbentuk grup musik ABS.
Bung Karno pernah berulah saat di Roma. Menyuruh para ajudan dan pengawalnya menggantikan musisi Italia yang saat itu memainkan Waltz untuk mengiringi acara setelah jamuan makan malam. Para tamu lain menari tari Ball-room, Bung Karno mengobrol dengan tuan rumah. Saat ajudannya mengambil alih para musisi Italia Bung Karno langsung melantai lalu berjoget. Bambang Widjanarko (1988: 85-86) memberi penjelasan, Bung Karno tidak menyukai dansa ala Barat karena beliau ingin menunjukkan kesenian bangsa sendiri (hal. 20).
Indonesia tak henti didefinisikan. Gagasan Priyadi menyelinap melalui Pendidikan, Politik, dan rawatan Kultural. Esai berarti kepekaan menanggapi berbagai persoalan dengan acuan referensi buku-buku. Priyadi tampak ampuh menanggapi masalah sosial budaya dengan mata perspektif yang mendalam. Karena itulah, daya kritiknya senantiasa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa menjadi diskursus pembangunan dan keintelektualan di Indonesia. Priyadi tidak ingin keburu atau gawat menanggapi berbagai persoalan di Indonesia dengan tema-tema besar. Ia berusaha mencari relasi lebih seserhana namun mendalam. Inilah yang kemudian membuat esai-esainya di buku ini pantas menjadi bacaan remeh dengan kadar gagasan yang justru terlihat lebih pokok karena berangkat dari pengamatan kehidupan sosial sekitar dan didukung dengan referensi.
Kita beralih ke esai Sawah. Priyadi mengisahkan sawah sejak masa sebelum kemerdekaan. Sawah pernah menjadi bagian penting dari obsesi kolonial. Berbagai kebijakan memihak kepentingan pasokan beras bagi negara kokonial meski beresiko dera kemiskinan orang-oran Pribumi. Sawah adalah suluh bagi keberlangsungan hidup.
Berbeda di mata penyair sawah bagi penyair adalah salah satu sumber estetika yang tak habis digali dalam nalar imajinasi. Priyadi sengaja mengutip beberapa puisi bertema sawah seperti, puisi Petani Tua karya Dami N Toda dan Nyanyian Ladang karya Subagio Sastrowardoyo. Namun gagasan penting dalam esai ini adalah bagaimana nasib sawah belakangan ini.
Perhatian Priyadi terhadap sawah dan relasinya dengan orientasi pendidikan mutakhir serta gejala urbanisasi dapat dibaca dalam narasi berikut ini: Profesi petani adalah profesi yang masuk dalam imajinasi masyarakat sebagai profesi dengan strata bawah. Mereka berharap anak-anaknya nurut dengan instruksi orang tua sebagai bagian dari “berbakti†dengan bekerja di kantor, gaji tetap, berparfum wangi, pakaian parlente dan semoga juga, jika pulang ke kampung membawa mobil (hal. 35).
Pada batas tertentu, buku Priyadi dapat menjad acuan refleksi dalam hidup ber-Indonesia di tengah bisingnya jargon-jargon produktif spirit nasionalisme. Agar gagasan keindonesiaan tidak hanya terbaca dalam bagaimana mempertahankan pancasilah dalam semaian lakon politik, tapi dapat diwujudkan dalam kesadaran membaca ulang narasi Indonesia dari waktu ke waktu. Dan buku ini adalah salah satu cuilan untuk membaca itu.
* Senang menulis sejak kuliah dan aktif di LPM Dialektika STIT Al Karimiyyah. Kini coba berpetualang dengan buku.